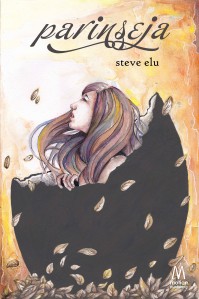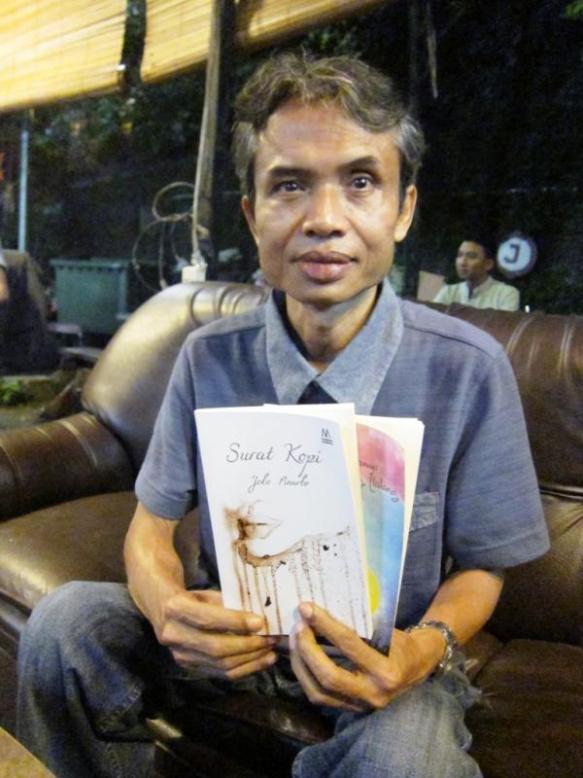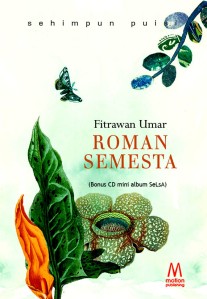Politik Identitas dan Ambivalensi “Dalam Lipatan Kain”
Oleh: Fariq Alfaruqi
Pendirian Balai Pustaka pada tahun 1908, lembaga buatan Belanda yang memberi pemisahan antara sastra yang bermutu (menggunakan bahasa Melayu tinggi) dengan bacaan-bacaan liar (menggunakan bahasa Melayu rendah); Kemudian, Berdirinya majalah Poedjangga Baroe sebagai anak ideologis dari Balai Pustaka, yang menjadi rujukan utama dalam mengkonstruksi sejarah sastra Indonesia; Atau, Masuknya arus pemikiran baru ke Indonesia yang ramai-ramai menolak modernisme dan sebagai bagian dari usaha perlawanan terhadap praktik-praktik represif pemerintahan Orba. Adalah periode-periode penting dalam perjalanan sejarah sastra Indonesia yang tidak bisa dilepaskan dari praktik kolonialisasi Belanda selama kurang lebih 350 tahun di Nusantara
Dengan menggunakan konsep mimikri yang dikemukakan Homi K Bhaba, bisa dilihat, bagaimana berdirinya lembaga Balai Pustaka dan eksisnya majalah Poedjangga Baroe, sebagai usaha-usaha menyejajarkan bangsa Indonesia sebagai bangsa terjajah, dengan Belanda sebagai bangsa penjajah. Usaha-usaha sastrawan dan kaum intelektual Indonesia yang berada dalam ‘lokasi kebudayaan’ yang serba pasca untuk memposisikan diri keluar dari tatanan budaya lama namun dengan tetap mempertahankan identitas Indonesia; Di satu sisi ingin keluar dari kekuatan hagemonik kolonial, namun di satu sisi tetap terikat dan memang terbentuk oleh kebudayaan tersebut. Sementara untuk poin ketiga, masuknya arus pemikiran baru ke Indonesia tersebut dipengaruhi, terutama oleh teori Edward Said (Orientalism), yang membongkar hagemoni kolonial (barat) terhadap penjajah (timur) dan praktik-praktiknya dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
Maka kondisi masyarakat sastra Indonesia hari ini juga tidak terlepas dari suatu keadaan yang disebut pascakolonial. Termasuk karya-karya yang muncul belakangan, atau yang biasa disebut dengan sastra mutakhir. Ania Loomba menyatakan, secara umum pascakolonial adalah sindrom kolonial, yang bentuknya sangat beragam dan barangkali tak terelakkan bagi mereka yang dunianya telah ditandai oleh praktik kolonialisme. Konsep ini di satu pihak dapat berarti era atau zaman, di pihak lain juga dapat berarti teori. Sebagai teori, pascakolonialise dibangun atas dasar peristiwa sejarah terdahulu, dalam kasus Indonesia, berarti pengalaman pahit bangsa Indonesia selama kolonialisme Belanda.
Melalui cara pandang ini saya akan coba membaca puisi-puisi Esha Tegar Putra yang terhimpun dalam buku kumpulan puisi Dalam Lipatan Kain (Motion Publishing, 2015). Melihat bagaimana sebuah diskursus yang hierarkis oposisional dibentuk (konstruksi lembaga-lembaga model kolonial) tersebut dilanggar dalam sebuah teks sastra mutakhir. Atau malah antara yang opisisional dengan yang terpecah, yang pusat dengan yang pinggir, atau yang barat dengan yang timur, justru tumpang tindih, membentuk suatu bentuk yang ambivalen
Lokalitas dan Politik Identitas.
Pembacaan pada tataran heuristik menunjukkan adanya beberapa kecendrungan bentuk yang khas dalam puisi-puisi Dalam Lipatan Kain ini. Pertama, penggunaan diksi seperti sangsai, sirah, pagu, mengupih, gadang, pulun, jilah, berdengkang, tuba,kerambil, dan lain sebagainya. Diksi-diksi tersebut berasal dari bahasa sehari-hari masyarakat Minangkabau, ranah kebudayaan di mana Esha Tegar Putra tumbuh dan berproses sebagai penyair. Yang menjadi pertanyaan awal adalah, kenapa diksi-diksi Minang mesti dimunculkan, padahal, jika dilihat dalam KBBI, akan ditemukan padanan kata dari diksi-diksi tersebut yang bisa mewakili makna secara semantis dan lebih universal. Seperti, sirah (merah), gadang (besar), pulun (gulung), jilah (putih bersih), berdengkang (panas menyengat), beberapa diksi lain justru merupakan bahasa minang yang di-Indonesia-kan secara serampangan, mengupih yang berasal dari maupiah, berdengkang dari badangkang, dan kerambil dari karambia.
Kedua, pola kalimat yang digunakan untuk membangun narasi dalam puisi-puisi tersebut, secara sintaksis juga menggunakan pola bertutur masyarakat Minangkabau, yang cendrung meletakkan subjek di tengah, bukan di awal kalimat. Contohnya, “…..ke arah hari lalu aku berjalan” (Ke Arah Hari Lalu), “Dari pitalah aku turun” (Kereta Singkarak). Ketiga, penyebutan nama-nama daerah yang secara geografis berada dalam daerah kultural Minangkabau. Seperti, “Kecuali angin berkisar tak sudah-sudah dari arah Pauh//deru batu terseret aliran deras batang Kuranji” (Angin dari Arah Pauh), “Ke pasar Aiaangek//jantung pisang itu hendak dibeli.//Dan aku jalan lagi//menurun dari Pandaisikek…” (Membeli Jantung Pisang).
Pemakaian diksi-diksi Minang dan usaha meng-Indonesia-kan beberapa diksi Minang secara serampangan dalam puisi-puisi Dalam Lipatan Kain akan menggiring kita pada pertanyaan, apa tendensi penyair ketika mengambil pilihan tersebut. Pertanyaan ini juga berlaku untuk kecendrungan yang kedua, mengadopsi cara bertutur masyarakat Minang ke dalam bentuk puisi. Melalui dua usaha ini, pembacaan awal yang bisa dikemukakan adalah, Esha berusaha membangun puisinya dengan piranti-piranti puitik yang bersumber dari sesuatu yang hidup, bergerak, dan mengalami perubahan dalam masyarakat di sekelilingnya. Hal ini juga dipertegas dari pilihan-pilihan tema yang diambil. Pada bagian awal puisi-puisi yang diikat dalam subjudul “Rumah Di Atas Gelombang” misalnya, persoalan-persoalan keluarga dan remeh-temehnya, seperti, berpisah sehari dengan istri (Ke Arah Hari Lalu), atau nyanyian menidurkan anak (Dendang Kapal Kandas), bisa juga istri yang sedang sakit (Di Tuba Kabut Asap), serta menunggu kelahiran seorang anak (Kelahiran Dendang). Sedangkan pada puisi-puisi subjudul “Kota Dalam Retakan Tempurung”, kota (terutama Padang), tempat penyair melanglang mencari-cari jalan kepenyairannya, dihadirkan beserta segala persoalan, kenangan, dan harapan yang berebut tempat di dalamnya, menjadi pilihan tematik penyair.
Dalam kerangka pascakolonial, saya melihat bahwa lokalitas yang dihadirkan Esha Tegar Putra dalam puisi-puisinya yang terhimpun dalam buku Dalam Lipatan Kain ini merupakan bagian dari wacana tandingan terhadap hagemoni kolonial, yang kemudian praktik-praktiknya dilanggengkan oleh pemerintahan represif Orde Baru, terutama dalam bidang bahasa dan sastra. Jika pada masa kolonial, bahasa Melayu tinggi berposisi sebagai dominan sementara bahasa Melayu rendah termarjinalkan. Maka pada masa pascakolonial, bahasa Indonesia—yang berasal dari bahasa Melayu tinggi yang mengambil posisi superior, sementara bahasa daerah yang inferior. Dengan menggunakan lokalitas sebagai bangunan utama puisi-puisinya yang dalam oposisional hierarkis kolonial justru berada pada posisi yang inferior, marjinal, pinggir, atau daerah ia telah ikut dalam diskursus yang berusaha menerobos garis demarkasi buatan kolonial. Secara lebih spesifik, misalnya, usaha meng-Indonesia-kan diksi Minang secara serampangan, adalah bentuk peniruan yang bertujuan untuk mengolok-olok bahasa Indonesia, yang dalam pengertian Homi K Bhaba sebagai mockery. Hal ini didukung oleh fakta sosiolinguistik yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau, dimana ketika menggunakan Bahasa Indonesia dengan dialek Minang kerap mendapat celaan oleh, baik itu masyarakat pusat maupun oleh masyarakat Minang itu sendiri.
Sementara, kecendrungan ketiga, yaitu, bagaimana kehadiran nama-nama tempat dalam kumpulan puisi Dalam Lipatan Kain sebagai usaha untuk membangun ruang yang bersifat lokal, juga merupakan wacana tandingan terhadap wacana hagemoni kolonial. Kali ini wacana kolonial hadir dalam bentuk karya-karya sastra barat yang menggambarkan dan sekaligus menyatakan bagaimana superiornya bangsa Eropa, yang kemudian diterjemahkan dan berpengaruh kuat pada novel-novel Indonesia pada awal-awal abad 20. Contoh karya-karya tersebut, di antaranya adalah, Monte Cristo. Novel ini adalah panorama aneka ruang yang ada di dalamnya. Ruang di dalam novel ini membentang dari belahan bumi barat ke sebelah timur, dari rumah orang yang sangat kaya dan mewah sampai ke rumah seorang nelayan yang miskin, dari istana raja dan rumah-rumah bangsawan yang terhormat sampai dengan sarang para penjahat. Keanekaan ruang-ruang partikular yang panoramik tersebut berimplikasi pada penegasan kembali gagasan mengenai imanensi narator dalam struktur naratif. Karena narator ada di mana-mana, semakin beraneka ruang yang ia masuki, semakin besar daya imenensinya, semakin besar pula kekuatan dan kekuasaannya, sebagaimana yang direpresentasikan oleh tokoh Monte Cristo. Sebaliknya, puisi-puisi Esha Tegar Putra justru memberi penegasan yang sebaliknya. Dengan menghadirkan ruang yang ‘kecil namun dikuasai dengan baik’ dalam bangunan-bangunan puisinya, ia justru menegaskan posisi yang bersebrangan dengan novel kolonial tersebut.
Lokalitas dan Ambivalensi
Ambivalensi adalah kondisi niscaya yang dihadapi oleh masyarakat negara bekas jajahan. Proses pencarian identitas yang dilakukan oleh masyarakat terjajah dihadapkan pada persoalan ketidakmungkinan untuk melepaskan diri secara penuh dari situasi pascakolonial. Homi K Bhaba menyebutnya sebagai ‘lokasi kebudayaan’ yang bersifat serba pasca, sebuah ‘wilayah antara’ yang di satu pihak ingin bergerak keluar dari kekinian masyarakat dan kebudayaan kolonial, dan dilain pihak tetap terikat pada dan berada dalam lingkungan permasalahan kekinian itu.
Maka, gerak politik identitas ke arah lokalitas, yang ada dalam kumpulan puisi Esha Tegar Putra, adalah contoh dari kondisi yang ambivalen tersebut. Di satu sisi, ia berusaha merusak kodifikasi dan standarisasi bahasa Indonesia, dengan memaksakan diksi-diksi Minang ke dalamnya, namun di sisi lain puisi-puisi tersebut masih menggunakan konstruksi bahasa Indonesia secara umum agar ia bisa dipahami oleh masyarakat di luar kultur Minang. Jika dilihat dari pola puisi yang kerap menggunakan paradoks, ironis, lebih sering sentimentil untuk menyelesaikan narasi yang dibangunnya, maka hal tersebut bisa diposisikan sebagai penegasan akan kondisi yang ambivalen tersebut, contohnya, “kita tertidur untuk terbenam di hari depan//kita berjalan untuk tearntuk pada kenangan.” ( Ke Arah Hari Lalu), Mengapung dan membenam. Hari lalu selalu bermain di atasnya//di antara hujan lebat dan panas berdengkang, di antara//air turun dan air naik…” (Menjauh Dari Kota). Pada kutipan pertama, bisa dilihat bagaimana jalan, dalam konteks pascakolonial merupakan pencarian, selalu menemukan benturan, apakah berdiam kemudian terbenam di hari depan, atau berjalan kemudian terantuk pada kenangan. Sedangkan pada kutipan kedua, akhirnya, posisi yang diambil adalah, berada di antara yang mengapung dan yang membenam, di antara hujan lebat dan panas berdengkang, atau di antara air turun dan air naik.
*)Tulisan ini didedahkan dalam seminar Pekan Kritik Sastra 2, 15-04-2015, dalam bentuk makalah.
*)Mahasiswa Sastra Indonesia Unand